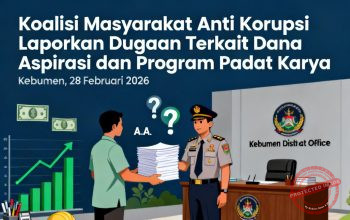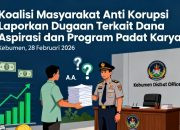Oleh MS.Tjik.NG
Tangerang_HARIANESIA.COM_Kasus meninggalnya seorang siswa SMPN 19 di Tangerang Selatan akibat bullying beberapa hari lalu kembali membuka luka lama bangsa ini. Fenomena kekerasan di sekolah bukan isu baru namun eskalasinya semakin mengkhawatirkan.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kekerasan antarpelajar, khususnya bullying, konsisten menempati posisi tiga besar kasus yang ditangani setiap tahun.
Pertanyaannya sederhana namun kompleks:
Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana menghentikan budaya kekerasan yang seakan menjadi normal ini?
Artikel ini berusaha memberikan pencerahan untuk pembaca: bahwa bullying bukan sekadar ulah anak-anak, melainkan produk dari ekosistem sosial yang sakit.
1. Bullying: Bukan Perilaku Individu, Tapi Gejala Sistem
Salah satu kesalahan terbesar masyarakat adalah memandang bullying sebagai:
kenakalan anak,
masalah personal,
konflik kecil sebaya, atau
bagian dari “proses pendewasaan.”
Padahal ilmu psikologi perkembangan, pedagogi, dan studi kekerasan menyatakan hal sebaliknya:
“Bullying adalah indikator kegagalan lingkungan anak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara”.
Ketika anak mampu:
menindas,
mempermalukan,
memukul,
mengancam,
bahkan menyebabkan kematian teman sebaya,
maka itu bukan hasil “kesalahan satu anak”, tapi hasil dari:
lemahnya kontrol sosial,
kegagalan pendidikan karakter,
kurangnya empati yang tidak dilatih,
budaya publik yang menormalisasi kekerasan,
serta sistem sekolah yang tidak memiliki perlindungan anak memadai.
Singkatnya, bullying adalah puncak gunung es dari lingkungan sosial yang membiarkan kekerasan berkembang.
-888-
2. Siapa yang Bertanggung Jawab? Analisis Multi-level
(1) Orang Tua — Sumber Pendidikan Emosional
Orang tua memegang peran sentral karena rumah adalah sekolah pertama pembentukan karakter. Banyak pelaku bullying berasal dari pola pengasuhan berikut:
kurang perhatian dan komunikasi emosional,
keluarga penuh konflik,
gaya parenting permisif (semua dibiarkan),
penggunaan gawai sebagai “pengasuh digital”,
kosongnya pendidikan moral sejak dini,
orang tua yang memberikan contoh perilaku agresif.
Kesalahan terbesar orang tua dalam era modern adalah:
“hanya memenuhi kebutuhan fisik (makan, sekolah, fasilitas), tetapi abai terhadap kebutuhan emosional, moral, dan empati”.
Akibatnya, anak tidak belajar:
menahan diri,
menghormati orang lain,
memahami perasaan sesama,
serta mengelola emosi secara sehat.
Tanpa fondasi ini, sekolah tidak punya cukup ruang untuk memperbaikinya.
(2) Sekolah — Arena Utama Interaksi Sosial Anak
Sekolah adalah tempat anak belajar 6–8 jam per hari. Ketika bullying terjadi, sekolah tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab, karena:
banyak sekolah tidak memiliki SOP anti-bullying,
guru lebih fokus akademik daripada karakter,
guru BK sering pasif dan hanya administratif,
kejadian bullying dianggap “biasa”,
area rawan (toilet, lapangan, lorong) minim pengawasan,
tidak ada mekanisme pelaporan rahasia.
Akibatnya, korban merasa tidak terlindungi, dan pelaku merasa tidak ada konsekuensi.
Sekolah wajib bertanggung jawab karena:
“pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi membentuk moral, empati, disiplin sosial, dan keamanan psikologis”
(3) Kelompok Teman Budaya Diam dan Penonton
Salah satu ciri khas kasus bullying di Indonesia:
selalu ada penonton,
ada yang merekam,
ada yang menertawakan,
tapi jarang ada yang menolong.
Budaya diam (bystander effect) ini adalah bukti bahwa:
empati kolektif menurun,
kekerasan dianggap hiburan,
anak takut dikucilkan jika membela korban,
media sosial memberi panggung untuk menjadikan kekerasan sebagai konten viral.
Dalam banyak studi, penonton yang diam juga dianggap bagian dari masalah, karena mereka memperkuat budaya permisif terhadap kekerasan.
-888-
(4) Masyarakat dan Media Digital — Normalisasi Kekerasan
Anak zaman ini tumbuh dengan konten:
prank kasar,
hinaan komedi,
kekerasan sebagai hiburan,
video bullying yang viral,
influencer yang merayakan agresivitas.
Tanpa edukasi literasi digital, anak menganggap kekerasan:
lucu,
normal,
keren,
tidak punya konsekuensi serius.
Tanpa pelindung psikologis dari orang dewasa, media digital menjadi faktor pembentuk moral yang sangat kuat bahkan lebih kuat dari keluarga dan sekolah.
(5) Negara dan Pemerintah Kebijakan yang Tidak Memadai
Indonesia masih belum memiliki:
Undang-Undang Anti-Bullying nasional yang komprehensif,
standar keamanan anak di sekolah,
psikolog pendidikan yang wajib hadir di sekolah,
mekanisme pelaporan yang aman,
sanksi tegas bagi sekolah yang lalai,
kurikulum literasi emosional yang memadai.
Kekerasan baru ditangani setelah korban parah atau meninggal, padahal negara harusnya hadir sebagai pelindung sejak awal.
3. Mengapa Bullying Semakin Parah?
Ada lima penyebab utama:
(1) Krisis Empati Generasi Digital
Interaksi berkurang, komunikasi pindah ke layar, dan empati emosional tidak dilatih.
(2) Pendidikan Karakter Tidak Serius
Sering hanya menjadi formalitas, tidak menyentuh akar psikologis anak.
(3) Orang Tua Kehilangan Fungsi Emosional
Sibuk bekerja dan menyerahkan pengasuhan pada gawai atau sekolah.
(4) Media Sosial Memberi Panggung Kekerasan
Kekerasan yang viral → ditiru → menjadi budaya.
(5) Tidak Ada Konsekuensi Tegas
Ketika pelaku tidak mendapat hukuman bermakna, bullying menjadi pola perilaku yang berulang.
4. Siapa Korban Sesungguhnya?
Korban utama tentu anak yang meninggal atau terluka.
Tapi dalam skala lebih besar:
korban adalah generasi yang kehilangan empati,
sekolah yang tidak aman,
masyarakat yang kehilangan nilai kemanusiaan,
dan bangsa yang meneruskan budaya kekerasan ke masa depan.
Jika hari ini siswa SMP sudah berani menghilangkan nyawa teman,apa yang akan terjadi ketika mereka dewasa dan memegang kekuasaan?
Bullying adalah akar masa depan kriminalitas, kekerasan rumah tangga, perundungan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Bagaimana Menghentikan Siklusnya? (Solusi Realistis)
(1) Untuk Orang Tua
Bangun komunikasi harian minimal 10–15 menit berkualitas.
Ajarkan empati melalui teladan.
Berikan batasan jelas dan konsekuensi tegas.
Awasi konten digital anak.
Ajari anak untuk tidak menormalkan kekerasan.
(2) Untuk Sekolah
Terapkan kebijakan Zero Tolerance terhadap bullying.
Sediakan pos pengawasan aktif di area rawan.
Terapkan Child Protection Policy resmi.
Libatkan psikolog sekolah.
Berikan program pemulihan hubungan (restorative justice).
(3) Untuk Pemerintah
Rancang UU Anti Bullying Nasional, seperti Jepang, Korea Selatan, atau Inggris.
Standarisasi sistem pengaduan nasional di sekolah.
Audit keamanan sekolah tahunan.
Sanksi administratif untuk sekolah yang lalai.
(4) Untuk Masyarakat
Hentikan tontonan kekerasan.
Dukung anak untuk berani melapor.
Jadikan komunitas sebagai pendukung moral.
-888-
6. Kesimpulan
Bro, bullying bukan sekadar masalah anak-anak.
Ia adalah cermin retak masyarakat kita.
“Kesalahan tidak terletak pada satu anak, tetapi pada seluruh ekosistem yang membiarkan kekerasan tumbuh”
Tanggung jawab penyelesaiannya ada pada:
orang tua,
sekolah,
masyarakat,
media,
dan negara.
Hanya dengan perubahan bersama, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berempati dan beradab.